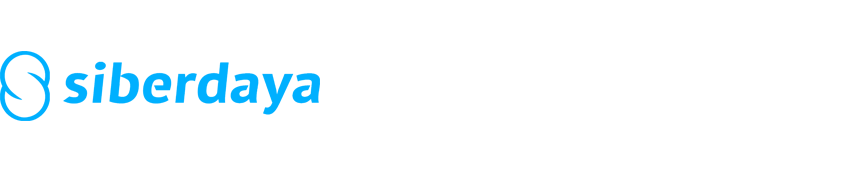Oleh: Bernard Batubara
Juan Aminardi, seorang “instrument builder” yang terhitung masih berusia muda ini, membawakan sebuah kisah dari George Town Festival, Penang, salah satu kota paling padat populasi dan paling urban, tempat ia residensi selama tiga bulan penuh, beberapa waktu lalu.
Dengan urbanisasi Penang dan populasinya yang padat, maka penting bagi posisi Juan untuk menyebarkan kabar baik dari Indonesia mengenai nasib alat musik tradisional, sebab laju arus peradaban memang tidak bisa dibendung lagi. Perputaran uang dan kebijakan publik yang menyertai dinamika politik geospasial-temporal pada konstelasi Asia Tenggara, dalam lingkup lebih luas yaitu Benua Asia dan Global Selatan, mampu membuat kita mudah lupa bahwa pada mulanya kita semua memang lah tradisional, bukan modern. Kita memodernkan diri kita berbekal apa yang kita sebut sebagai teknologi maju, yang datang dari Barat, untuk mendefinisikan kemajuan Timur.
Hal inilah yang ditentang oleh Juan Aminardi dengan membawakan instrumen yang diciptakannya sendiri, membangun alat musiknya sendiri dari nol, hingga ia berhak mementaskannya di negeri Jiran, Malaysia, sebuah tetangga bangsa-negara yang sering menjadikan Indonesia kiblat seninya.
Hal ini merupakan kabar baik yang dibawa Juan sepulangnya ia dari George Town Festival, ia menyampaikan di Pasar Purnama, saat kegiatan “Jam Berjam-jam” yang digelar oleh Balaan Tumaan di rangkaian pameran kulu kile’. Pada momen tersebut Juan membagikan pengalaman personalnya Dan mempertontonkan kebolehannya dalam memainkan alat musik yang ia bangun, serta mengajak audiens yang ada untuk turut memainkannya.
Frekuensi hibrid. Demikian tajuk yang Juan tawarkan saat keikutsertaannya di George Town Festival, Penang, dimana tajuk tersebut adalah sebuah frasa yang dirinya ingin kita ingat dalam memori kolektif bertetangga dengan Malaysia. Menyudahi perselisihan soal banyak hal, Indonesia dan Malaysia, toh, merupakan sebuah rumpun suku Melayu yang satu, di dalam garis-garis yurisdiksi kenegaraan yang memisahkannya, kedua negara ini bersatu dalam kesamaan identitas kesukuan, dan yang lebih indah lagi adalah, kesamaan ini ditandai dengan penampilan alat musik tradisional, seolah mengatakan kepada kita, bahwa memang yang namanya urban itu tidak sungguh-sungguh ada, minimal ia ada sebagai bayangan dari yang nyata, yaitu tradisi.
Urbanisasi dan tradisi merupakan petanda-petanda yang kita maknai sebagai dialektika tidak berkesudahan. Musik Juan adalah penanda memori bersama yang akan serta-merta jadi monumen atau tugu ingatan yang akan abadi seiring kita menjadi bagian dari dialektika sejarah materil alat-alat musik manusia yang Juan buat.
Juan Arminandi menggunakan metodologi ala seorang etnografer dan antropolog dalam merampungkan proyek pembangunan alat musiknya sendiri. Ia bertemu dan meriset bagaimana pekerja kelas ekonomi bawah yaitu tukang dan para pengrajin kayu dan besi.
Konseptualisasi ide Juan menjadikan pengalaman meriset ini jadi sebuah karya yang dapat dinikmati publik luas. Tidak cuma warga Malaysia dan Indonesia, tapi berbagai sub-suku yang melatarbelakangi hibriditas multikulturalisme yang tandanya adalah eksisnya heterogenisme budaya, untuk melawan atau mengoposisi hegemonisme budaya.
Pada dasarnya, yang Juan lakukan adalah sebuah sindikat baik yang pula beritikad baik untuk menjembatani jarak antara kemajuan budaya Indonesia dan Malaysia, melalui praktik alat musik tradisional sebagai antitesa dari kemajuan peradaban Barat, yang selalu menjadikan Timur atau bahkan Asia Tenggara sebagai proksi (“proxy war”) dagang dalam kebudayaan. Sebuah harapan cerah bagi pesimisme warga kita atas hal-hal yang membawa apatisme dan skeptisisme akhir-akhir ini terkait pergulatan politik kedaerahan, pusat, bahkan juga tidak lupa dilatarbelakangi pergolakan geopolitik global, tentu dalam kancah skena kebudayaan. []